Program pendidikan desain grafis di Amerika dapat di bagi kedalam dua kategori besar: process schools dan portfolio schools. Sekolah proses menekankan pada bentuk, artinya pemecahan masalah visual yang disetir oleh bentuk. Latihan-latihan awalnya sederhana: menggambar huruf, menerjemahkan bentuk-bentuk tiga dimensi ke citra dua dimensi yang berkualitas kontras ideal, dan dasar fotografi still-life.
Pada tingkat pertengahan, latihan-latihan formal tersebut dikombinasikan dengan berbagai cara: padukan gambar flute dengan gambar huruf N, padukan huruf N dengan foto sepatu ballet.
Pada tahap akhir kombinasi-kombinasi di atas dijelmakan jadi “sebuah karya” desain grafis: Huruf N ditambah gambar flute ditambah foto sepatu ballet ditambah huruf judul Univers 42pt, maka sim salabim, jadilah sebuah poster untuk Rudolf Nureyev. Maka ketika desainer alumni dari situ dapat proyek mendesain, misalnya poster pameran karya Thomas Edison, maka dia akan cenderung untuk berbalik ke cara: padukan huruf E, dengan gambar camera, foto bohlam, dll, dicampur jadi satu. Begitulah urat pikir sekolah proses, yang akarnya menancap di Kunstgewerbeshule di Basel Swiss.
Sekolah portfolio,
Menurut para pendukung portfolio school, metode desain process school itu sok tinggi, tertutup, rahasia, dan tidak membumi. Menurut para pendukung process school, metode portfolio school berselera rendah, murahan dan tidak asli.
Anehnya alumni-alumni dari kedua sistem sekolah tersebut sama lakunya. Perusahaan logo menyenangi alumni sekolah proses, buat di suruh bikin logo manual yang super tebal. Perusahaan packaging menyenangi lulusan portfolio school, buat di suruh bikin comprehensive desain yang super cantik, dan bikin ratusan alternatif desain yang stylish untuk menyenangkan client yang bingung memilih.
Masalahnya adalah, kedua jenis program ini sama saja: yaitu mementingkan bagaimana tampang atau penampilan desain grafis, bukan pada permaknaannya. Dalam hal permaknaan, process school membual dengan kalimat-kalimat seputar “semiotics”. Sedangkan portfolio schools membual dengan “conceptual problem solving”. Namun pada dasarnya semua kalimat tersebut melayang di awang-awang budaya.
Hampir pada semua program pendidikan, bisa jadi siswa belajar desain grafis tanpa sedikit pun pernah mendalami perihal seni murni, sastra dunia, sains, sejarah, politik atau disiplin-disiplin lain yang semuanya mengikat kita di dalam budaya sehari-hari.
Memangnya kenapa? Apa perlunya desainer grafis berhubungan dengan semua urusan tadi? Toh perusahaan-perusahaan mencari desainer grafis terlatih, bukan perlu penulis atau pengamat budaya?
Pada awalnya kekurangan tersebut tidak terasa, memang para lulusan baru tidak perlu lebih tahu mengenai perekonomian ketimbang tukang servis tv, yang penting asal mereka punya skill teknis, that’s it, cukup. Namun setelah
Beberapa desainer mengisi ompong pendidikan itu belajar sendiri, banyaknya sih mengarang. Namun rata-rata karya desain masa kini, dibuat oleh para desainer yang tetap setia merancang dengan cara sebagaimana ajaran sekolah dulu: mendesain sebagai upacara pemujaan di atas altar visual.
Karya-karya perintis desain grafis dari jaman empat puluhan dan
Di sisi lain, sistem pendidikan modern, pada hakekatnya bebas dari nilai: setiap masalah desain dapat dipecahkan dengan solusi visual yang berdiri terpisah dengan kaitan budaya mana pun.
Contoh kasus: dengan enak dan langsung saja (dibayar mahal lagi) desainer masa kini terima proyek untuk meng-upgrade sebuah logo classic dari suatu merek soft drink, dibikin up to date, tanpa mengindahkan makna logo tersebut dalam kaitan budaya di jamannya. Renovasi total, gak kepikir sedikit pun untuk mengatakan tidak.
Kini, hasrat para pendidik desain sepertinya mengarah ke teknologi, buta komputer ditakuti bakal jadi kendala bagi lulusan. Sebenarnya, masalahnya bukan di situ, ada kebutaan lain yang lebih luas. Jika para pendidik tidak menemukan cara untuk membuka wawasan siswa dalam dunia budaya penuh makna, maka para alumni akan terus bicara dengan bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh teman sekelasnya. Dan pada akhirnya para desainer, semakin hari dan semakin hari, hanya bisa berkomunikasi dengan diri sendiri.
04 Maret 2009
why designers can’t think
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
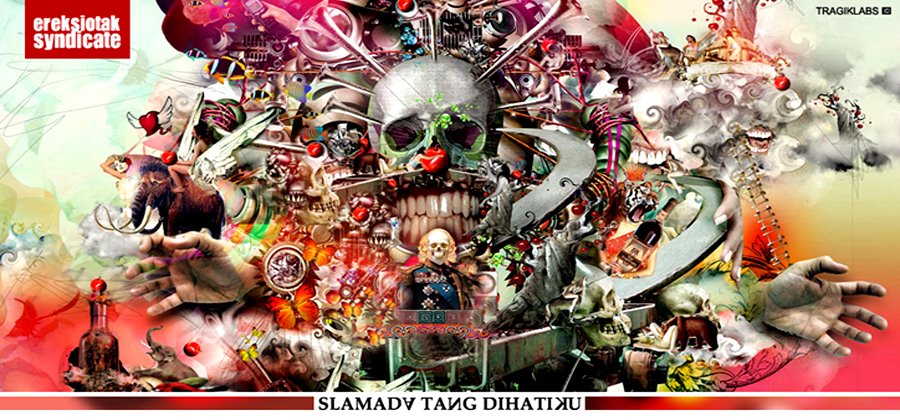





Tidak ada komentar:
Posting Komentar